Sejauh manakah anda bersetuju dengan kenyataan-kenyataan berikut:
A: Malaysia adalah Tanah Melayu dan orang Melayu adalah tuan dan pemilik sebenar.
B: Malaysia adalah milik semua warganegara yang sah tidak kira dari Semenanjung, Sabah atau Sarawak.
Soalan-soalan sebegini diajukan dalam satu soal selidik untuk mengukur sejauh manakah sifat keterangkuman masyarakat Melayu.
(Soal selidik ini dijalankan dari 1 Oktober hingga 24 Disember 2018, oleh Dr Wong Chin Huat dari Penang Institute dan Ilham Centre.)
Andaiannya, responden yang bersetuju dengan kenyataan A menuntut dominasi eksklusif Melayu ke atas Malaysia, manakala responden yang bersetuju dengan kenyataan B mengiktiraf Malaysia sebagai negara multietnik yang dikongsi bersama.
Secara logiknya, kenyataan A dan B membawa maksud yang saling bercanggah, maka responden yang bersetuju dengan A, akan menolak B; begitu juga dengan sebaliknya.
Namun, hasilnya menyanggah andaian sebegini. Daripada 2,614 orang responden Melayu-Muslim yang ditemu bual, 90% (dengan wajaran) bersetuju dengan A; sementara 81% daripada responden yang sama, bersetuju dengan B. Dengan kata lain, lebih dua pertiga responden bersetuju dengan kedua-dua A dan B.
Mujur institusi kaji selidik yang terbabit bersikap jujur untuk membentangkan kedua-dua hasil dapatannya, lantas memberi gambaran yang lebih menyeluruh untuk ditafsirkan. Cuma kita kurang pasti, dari sudut mana media memfokuskan kameranya.
Persepsi yang dibentuk media
Bayangkan, seandainya media yang membuat liputan pembentangan kaji selidik ini menonjolkan “90% Melayu mendakwa Malaysia dimiliki Melayu” sebagai tajuk beritanya, sudah tentu ia membentuk satu persepsi bahawa Melayu tidak bersedia untuk berkongsi tanah air ini dengan etnik lain. Tetapi, jikalau media menonjolkan “81% Melayu bersetuju Malaysia milik semua rakyat Malaysia”, suasananya akan berbeza.
Ringkasnya, data daripada kaji selidik yang sama, boleh dimanipulasikan untuk membentuk persepsi yang berbeza. Persoalannya, tajuk berita manakah yang lebih sensasi untuk menggoda “klik” netizen, tatkala “klik” menjadi antara kayu ukur untuk menentukan harga ruangan iklan di medianya? Atau, seandainya satu eksperimen dijalankan, dengan dua kandungan berita yang sama dibubuhkan tajuk yang berbeza seperti di atas, manakah yang lebih luas ditularkan di media sosial?
Kita semua dapat menjangkakan jawapannya, barangkali juga kesannya. Berita dengan tajuk “90% Melayu menuntut hak milik tanah air Malaysia untuk Melayu”, akan ditularkan seluas-luasnya, dalam kalangan Melayu dan bukan Melayu. Masyarakat bukan Melayu akan melontarkan “tuduhan rasis” semarah-marahnya, disusuli dengan keluhan sehampa-hampanya. Melayu yang dituduh rasis akan melenting, kerana asalnya dua pertiga daripadanya (jikalau mengikut angka kaji selidik tersebut) bersedia untuk berkongsi tanah air ini bersama etnik lain, tetapi kini mereka dituduh sebagai “rasis”. Akhirnya mereka ditolak beransur-ansur ke arah menjadi rasis.
Sentimen negatif berlegar-legar, sedangkan suasana masyarakat akan berbeza seandainya kita memilih “81% Melayu bersetuju Malaysia dimiliki semua rakyat bersama” sebagai tajuknya. Apapun, cabaran media bukan untuk memilih antara persepsi positif dengan negatif yang ingin dibentuk, tetapi bagaimana untuk menggambarkan realiti kepada pembacanya. Kita tidak mahu sentimen perkauman diapi-apikan untuk mencetuskan syak wasangka dalam kalangan rakyat; pada masa yang sama, kita juga tidak harus mewujudkan suasana “feel good” yang direka-reka, menafikan kegusaran yang sememangnya sedang membara dalam masyarakat kita.
Bagaimana pilihan manusia dipengaruhi?
Jadi, apakah gambaran yang paling dekat dengan realiti? Menurut penyelidiknya, Dr Wong Chin Huat, bacaan kita mungkin lebih tepat seandainya mengambil 10% yang menolak A, dan 19% yang menolak B, dengan mengambil kira faktor psikologi manusia yang lebih mudah untuk mengiyakan daripada menidakkan. Pegangan atau kepercayaan seseorang itu memacu sedikit momentum agar dirinya menongkah arus untuk menyatakan bantahannya.
Saya bersetuju dengan tafsiran Dr Wong Chin Huat, dan ingin memanjangkan sedikit perbincangan daripada itu. Kebanyakan masanya, manusia tidak berpendirian, dan malas untuk membuat keputusan – dari hal yang remeh-temeh, hinggalah isu yang berat dan rumit. Contohnya, kita tidak tahu apa untuk dimakan, tetapi seandainya kebetulan dihulurkan voucher diskaun 25% untuk KFC, dan voucher diskaun 40% untuk Mekdi pada masa yang sama, maka kebanyakan kita akan berakhir di Mekdi.
Dalam kes ini, apakah pengguna telah membuat keputusannya sendiri? Ya, tetapi keputusannya dipengaruhi. Malah pengguna mengambil jalan mudah, membuat pertimbangan berdasarkan nilai wang ringgit, dengan andaian bahawa potongan 40% lebih berbaloi berbanding potongan 25%. Itu pun belum dikira apakah kita benar membayar lebih murah di Mekdi kerana harga asalnya perlu dijadikan pertimbangan. Jauh lagi soal kerangupan, juga nilai khasiat ayam goreng yang dihidangkan.
Biar kita lanjutkan dengan kes yang sedikit lebih rumit. Pernah majalah The Economist menawarkan pakej-pakej langganan tahunannya seperti berikut:
A. Edisi digital – AS$59/tahun
B. Edisi cetakan – AS$125/tahun
C. Edisi digital+cetakan – AS$125/tahun
Seorang pensyarah menghidu sesuatu di sebalik iklan ini, lalu mengambil keputusan untuk menjalankan satu eksperimen dalam kalangan 100 orang penuntutnya. Hasilnya, majoriti memilih pakej C, dan tiada yang memilih pakej B. Seterusnya pensyarah itu menyingkirkan pakej B, untuk dipilih penuntutnya hanya antara pakej A dengan C. Kali ini, pakej A menjadi pilihan majoriti, menewaskan C.
Jelas, pakej B sebenarnya tidak ditawarkan untuk pilihan, tetapi untuk mempengaruhi pengguna supaya memilih pakej C. Pengguna tidak tahu apakah pilihan asalnya, dan hanya mampu memilih melalui perbandingan. Di sini pengiklan mengambil kesempatan untuk mempengaruhi keputusan pengguna dengan menyelitkan pakej B.
Seandainya ini yang dinamakan psikologi ekonomi, barangkali kita perlu bertanya, apakah wujud perilaku yang mirip, yang boleh dibaca sebagai “psikologi politik”?
“Psikologi politik”
Pernahkah kita terfikir, bahawa seandainya kita diberi pilihan, antara Dr Dzulkefly Ahmad (Amanah) dengan Dr Adham Baba (Umno), siapakah yang lebih kita yakin akan kelayakannya sebagai menteri kesihatan? Antara Bersatu dengan PKR, parti manakah yang lebih kita yakin untuk mentadbir, jikalau dibariskan Mohd Redzuan Md Yusof, Rina Harun, Mohd Radzi Md Jidin dan sekutunya, untuk dibandingkan dengan Saifuddin Nasution, Fuziah Salleh, Lee Boon Chye dan sekutunya?
Seandainya dinilai hanya berdasarkan prestasi, barangkali Dr Dzulkefly Ahmad jauh mendahului; begitu juga dengan PKR dalam perbandingannya dengan Bersatu. Namun demikian, jikalau dinilai dari segi persepsi, sudah tentu Dr Dzukefly Ahmad jauh ketinggalan berbanding Dr.Adham Baba, apabila parti yang diwakilinya diambil kira. Malah, dalam babak perbandingan antara parti politik, rakan sekutunya akan diambil kira sebelum dibuat keputusan.
Pernahkah kita terfikir, bahawa mungkin pakej B politik diselitkan, untuk mempengaruhi keputusan kita? Misalnya, kita diberi pilihan:
A. Umno (sekutu PAS)
B. DAP (sekutu Amanah)
C. Amanah (sekutu DAP)
Atau, voucher politik dihulurkan untuk mempengaruhi pilihan kita? Contohnya, kita diberi pilihan:
A. Bersatu (dalam Muafakat Nasional dengan 100% Melayu)
B. PKR (dalam Pakatan Harapan dengan 35% Melayu)
Barangkali kurang jitu dibandingkan sebegitu, lantaran sistem politik yang menuntut agar kita mengambil kira faktor parti calon dan gabungannya. Namun demikian, persoalan yang ingin diketengahkan adalah, apakah kita cukup peka dengan elemen yang cuba digunakan untuk mempengaruhi keputusan kita, sama ada dalam bentuk pakej B, mahupun voucher, sehingga kita mengetepikan pertimbangan faktor kecekapan, idealisme, integriti, keberkesanan, ketelusan dan sebagainya, yang ditampilkan oleh calon dan parti?
Dan seandainya kita memahami taktik-taktik sebegini, apakah kita akan terkejut apabila faktor DAP diperbesarkan, dan sentimen perkauman dibakar sewenang-wenangnya? Jadi, tepuk dada tanya selera, apakah pilihan kita benar-benar pilihan kita?
*Tulisan ini disiarkan di Malaysiakini (2 September 2020): https://www.malaysiakini.com/columns/540970
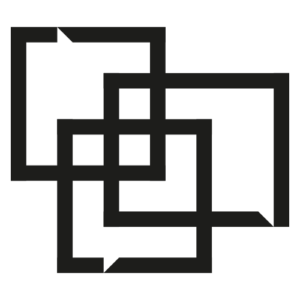


Facebook Comments